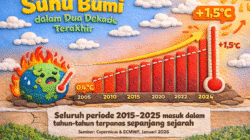INIBORNEO.COM, Pontianak – Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) merupakan salah satu intervensi kesehatan paling efektif dalam mencegah penyakit menular pada anak usia dini. Melalui imunisasi, anak-anak terlindungi dari berbagai penyakit berbahaya seperti polio, campak, hepatitis B, TBC, dan difteri. Pemerintah Indonesia bahkan menetapkan target cakupan IDL sebesar 100 persen sebagai bentuk komitmen terhadap pemenuhan hak kesehatan setiap anak.
Di Kalimantan Barat, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) justru menunjukkan tren penurunan yang mengkhawatirkan. Mengutip data Dinas Kesehatan Kalimantan Barat yang dilaporkan oleh Antaranews, rata-rata cakupan IDL pada 2024 hanya mencapai 48,7 persen yang mana turun drastis dari 74,3 persen pada tahun sebelumnya. Penurunan ini mencerminkan adanya hambatan serius dalam aspek logistik, infrastruktur, serta pelaksanaan layanan kesehatan dasar di lapangan.
Cerita Saras dan Ana: Buruh Perempuan dan Keterbatasan Layanan
Matahari mulai menyengat saat jam menunjukkan pukul 10 pagi. Saras (25) masih sibuk mengurus anaknya yang belum genap dua tahun. Dari rumah sederhananya, tak jauh dari mess buruh lain di kawasan perkebunan, tampak deretan pohon sawit membentang. Sementara itu, tempat yang biasanya dipenuhi tumpukan tandan kosong terlihat lengang karena panen telah usai.
Sebagai buruh harian lepas di perusahaan sawit PT Rezeki Kencana Prima (RKP), Kabupaten Sanggau, Saras menghadapi kesulitan untuk mendapatkan layanan imunisasi bagi anaknya yang masih balita.
“Sekarang jarang imunisasi, tinggal di sini susah. Tenaga medisnya juga kurang. Kadang ada, kadang enggak,” ujar Saras dengan suara pelan.
Dulu, ada seorang bidan dari Puskesmas Tayan yang rutin membuka praktik di sekitar permukimannya. Kehadiran sang bidan membuat layanan kesehatan lebih mudah dijangkau. Namun sejak bidan tersebut pindah kembali ke Jakarta, layanan itu pun menghilang. Kini, satu-satunya akses imunisasi terdekat berada di Perum atau puskesmas pembantu, sekitar sepuluh kilometer jauhnya. Jarak menuju puskesmas menjadi tantangan tersendiri bagi warga yang tak memiliki kendaraan pribadi.
Jalan yang harus dilalui sebagian besar telah rusak yakni lubang-lubang dalam menganga di sejumlah titik, membahayakan pengendara, terutama pengguna sepeda motor. Minimnya penerangan membuat perjalanan di malam hari terasa lebih berisiko. Di sepanjang rute itu, truk-truk besar pengangkut tandan sawit berlalu-lalang tanpa henti, mempersempit ruang gerak dan menambah tekanan, terutama dalam kondisi darurat seperti saat membawa pasien yang membutuhkan pertolongan cepat.

“Kalau ada tempat pelayanan di sini kan enak. Tapi enggak ada, jauh juga ke sana. Harus ke Perum, itu pun kadang kadernya kurang ramah,” tuturnya.
Meski menghadapi banyak kendala, Saras tetap bertekad untuk menyelesaikan imunisasi anaknya. “Dari lahir sampai lima tahun itu harusnya lengkap. Aku sih percaya aja, yang penting anak sehat,” katanya mantap.
Sebagai buruh perempuan, Saras harus membagi waktu antara bekerja dan mengurus anak. Ia bekerja sebagai tukang nangkos atau penyusun tandan kosong sawit dengan target harian satu dam, tergantung ketersediaan bahan. Tak selalu mudah karena kadang ia harus membawa anak ke kebun karena tidak ada yang menjaga.
“Kalau nangkos, kadang anak tinggal di bawah, kadang ikut. Tapi anakku enggak rewel, enak diajak,” ujarnya sambil tersenyum kecil.
Cerita Saras bukan satu-satunya. Ana Susilowati (38), mantan buruh lepas di PT Rezeki Kencana Prima (RKP), juga mengalami hal serupa. Pagi itu, ia tengah menyiapkan dagangannya yakni merentangkan tali-tali untuk menggantung minuman sachet di gazebo rumah sederhananya. Warung kecil di beranda rumah itu kini menjadi sumber tambahan penghasilan setelah ia berhenti bekerja di perkebunan sawit empat tahun lalu.
Ana mengenang masa-masa saat masih aktif bekerja di kebun. Meski tengah hamil tua, ia tetap mengangkat tandan sawit. Setiap hari, sejak pukul enam pagi hingga sepuluh, ia berada di kebun. Siangnya ia sempat pulang untuk mengantar anak ke posyandu, sebelum kembali bekerja lagi hingga sore. Dalam sehari, ia bisa menyusun hingga dua belas hingga lima belas ton tandan kosong.
“Apapun kerjaan kita, kalau soal anak, kita harus usahakan yang terbaik,” ujarnya sambil merapikan tali rafia untuk mengikat kantong-kantong minuman yang ia jual di warung sederhana miliknya.
Ana tak ragu soal imunisasi. Menurutnya, layanan dari puskesmas adalah bagian dari tanggung jawab negara. “Karena ini dari pemerintah, pasti baik. Yang penting dari puskesmas resmi,” tegasnya.
Namun, ia menyayangkan tidak adanya dukungan dari pihak perusahaan. “Kalau dari PT, enggak ada yang menyuruh atau mengadakan. Semua inisiatif kita sendiri sebagai orang tua,” tambahnya.
Dalam situasi paling sulit, Ana bahkan pernah membawa bayinya ke kebun dan menaruhnya di atas karpet di bawah pohon sawit, lengkap dengan bekal makanan dan mainan seadanya. “Aku alas pakai karpet, taruh anak di bawah pohon, kasih makan, kasih mainan, gitu aja,” kenangnya.
Fasilitas kesehatan di tempat mereka bekerja praktis tidak tersedia. Klinik yang ada pun milik swasta dan tidak menjangkau kebutuhan anak buruh secara khusus. Bantuan pemerintah tidak datang secara rutin, kecuali dalam bentuk undian sembako atau air bersih, bantuan yang tidak menyentuh kebutuhan dasar seperti imunisasi.
Kondisi makin sulit bagi warga yang tinggal di rumah-rumah terpencil. Jarak antara satu rumah ke rumah lainnya cukup jauh, dengan sebagian di antaranya berada di tengah-tengah blok kebun tanpa akses kendaraan umum. Dalam keadaan darurat, seperti ibu hamil yang hendak melahirkan, keluarga harus menempuh jarak cukup jauh hanya untuk meminta pertolongan, sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan panjang ke fasilitas kesehatan terdekat.
Ketapang dan Sanggau: Luas Kebun Sawit, Minim Layanan Kesehatan
Sebagai dua kabupaten dengan kontribusi terbesar dalam industri sawit Kalimantan Barat, Ketapang dan Sanggau justru menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan layanan kesehatan dasar bagi anak-anak. Di Kabupaten Ketapang, cakupan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada balita hanya mencapai 43 persen pada tahun 2024, sebagaimana tercatat dalam laporan kuartal terbaru Petarisi Kopie. Angka ini jauh dari target nasional dan memperlihatkan ketimpangan antara pertumbuhan sektor industri dengan jaminan hak dasar anak atas perlindungan kesehatan.
Sementara itu, situasi di Sanggau pun tak jauh berbeda. Meski pemerintah daerah telah merilis data jumlah bayi yang mendapat imunisasi melalui portal resmi, tak ditemukan angka pasti terkait cakupan IDL. Dalam dataset bertajuk “Jumlah Bayi yang Mendapat Imunisasi di Kabupaten Sanggau Tahun 2024”, tidak dijelaskan secara spesifik berapa banyak anak yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian imunisasi dasar. Ketidakjelasan ini menyulitkan publik maupun pemangku kebijakan untuk menilai sejauh mana layanan kesehatan anak telah dijalankan secara merata di wilayah tersebut.
Padahal, secara ekonomi, Ketapang dan Sanggau memegang peranan strategis. Ketapang tercatat sebagai daerah dengan luasan perkebunan sawit terbesar di Kalimantan Barat yang mencapai 764 ribu hektare, disusul Sanggau dengan lebih dari 300 ribu hektare. Jumlah penduduk di kedua kabupaten juga signifikan, masing-masing mencapai 599.890 jiwa di Ketapang dan 510.412 jiwa di Sanggau, menurut data BPS 2024. Di tengah dominasi industri sawit, ribuan anak justru belum memperoleh akses imunisasi lengkap yang seharusnya menjadi hak dasar mereka.
Pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh komoditas sawit ternyata belum dibarengi dengan pemerataan layanan publik. Di lapangan, akses terhadap imunisasi dasar kerap terhambat oleh keterbatasan tenaga kesehatan, jauhnya jarak antara permukiman buruh dan fasilitas layanan, hingga kondisi infrastruktur jalan yang rusak. Ketimpangan ini menjadi cerminan lemahnya integrasi antara pembangunan ekonomi dan penyediaan layanan dasar, terutama di wilayah yang menopang komoditas ekspor unggulan seperti sawit.
Fasilitas Pustu yang Minim
Di sisi lain, Yuni Ernawati, bidan di Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Subah, mengungkap sejumlah tantangan teknis dalam pelaksanaan imunisasi di lapangan. Desa Subah sendiri tak jauh dari lokasi PT RKP.
Menurut Yuni, sebagian besar keluarga buruh di desa tersebut merupakan pendatang. Mobilitas mereka yang tinggi menyulitkan pelacakan status imunisasi anak-anak. “Kadang baru imunisasi satu kali, anaknya sudah diajak pulang kampung. Susah untuk dilacak lagi,” ucapnya.
Keluarga buruh yang menetap cenderung memiliki cakupan imunisasi tinggi, bahkan hampir mencapai 100 persen. Namun yang berpindah-pindah sering meninggalkan jadwal imunisasi tak lengkap. Beberapa orang tua juga sempat menolak imunisasi karena anak mengalami demam setelah disuntik.
“Sekarang masyarakat juga mulai paham. Memang kadang datangnya terlambat dari jadwal, tapi sebagian besar tetap lanjutkan imunisasi anaknya,” tambahnya.
Sayangnya, hingga kini belum ada layanan jemput bola atau imunisasi keliling di sekitar desa tersebut. Pelayanan hanya tersedia saat posyandu, yang masih menumpang di balai dusun atau gereja. Warga harus datang sendiri ke lokasi. Dengan pekerjaan berat, minim transportasi, dan beban ganda sebagai ibu sekaligus buruh, ini menjadi kendala serius.
Masalah lain adalah keterbatasan infrastruktur. Di Puskesmas Pembantu (Pustu) tempatnya bertugas, belum tersedia listrik tetap. Mereka menggunakan genset pribadi, sehingga tidak memungkinkan menyimpan vaksin.
Suasana puskesmas yang menjadi rujukan terdekat pun tak luput dari sorotan. Saat dikunjungi pada siang hari, bangunan puskesmas sudah dalam kondisi tertutup. Jendela-jendelanya tak dilengkapi gorden, memperlihatkan bagian dalam ruangan yang tampak kosong dan minim aktivitas. Dari luar, hanya terlihat beberapa kursi plastik dan meja tua. Tidak tampak alat kesehatan yang memadai untuk menangani kasus darurat. Kondisi ini memperkuat kesan bahwa fasilitas kesehatan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan medis dasar masyarakat di sekitarnya, apalagi dalam situasi genting seperti persalinan atau gawat darurat anak.

“Kalau ada posyandu, baru kami ambil vaksin dari puskesmas. Jadi stok tidak bisa disimpan,” jelasnya.
Koneksi internet pun tidak stabil, menyulitkan proses pelaporan dan pencatatan imunisasi. Padahal pemerintah tengah mendorong sistem pencatatan daring melalui aplikasi nasional.
Yuni berharap Pustu Desa Subah ke depannya memiliki bangunan tetap dan perlengkapan memadai, terlebih dengan adanya kebijakan Posyandu Integrasi Layanan Primer (ILP). Namun, hingga kini belum ada anggaran desa yang dapat dialokasikan untuk pembangunan fasilitas tersebut.
PT SJAL: Jarak Jauh, Transportasi Sulit
Di PT SJAL, situasinya lebih rumit. Banyak buruh belum mengimunisasi anak mereka karena jarak, minim transportasi, dan kurangnya informasi. Sebagian orang tua beranggapan anak tetap sehat tanpa imunisasi.
Ketua Federasi Serikat Buruh Kebun Sawit Kalbar (FSBKS Kalbar), Yublina Yuliana Oematan, yang juga bekerja sebagai buruh di PT SJAL, menegaskan bahwa kesadaran para buruh perempuan terhadap pentingnya imunisasi sebenarnya cukup tinggi. Namun, keterbatasan akses membuat mereka kesulitan mewujudkannya.
“Banyak hambatan yakni mulai dari jarak tempuh, tidak adanya dukungan transportasi, hingga sikap abai perusahaan dan minimnya peran pemerintah sehingga membuat anak-anak buruh terancam kehilangan hak dasarnya atas imunisasi,” ujarnya.
Puskesmas terdekat dari lokasi kerja maupun tempat tinggal buruh berjarak sekitar 15 kilometer. Bagi buruh harian lepas yang tidak memiliki kendaraan pribadi, ini menjadi tantangan besar. Jika ingin membawa anak ke puskesmas, mereka harus izin tidak masuk kerja yang artinya kehilangan pendapatan hari itu.
“Izinnya sih boleh, tapi tidak dibayar. Jadi kadang terpaksa ditunda, apalagi kalau harus jalan jauh,” tambah Yublina.
Ketiadaan transportasi menjadi masalah yang terus berulang. Di kawasan perkebunan terpencil seperti PT SJAL, angkutan umum nyaris tak tersedia. Para buruh perempuan, terutama yang berasal dari luar daerah, tak punya pilihan selain mengandalkan diri sendiri.
Pemerintah daerah pernah menjalankan layanan jemput bola, namun sifatnya hanya sementara, dan hanya muncul saat terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) seperti pandemi COVID-19 atau lonjakan kasus malaria. Untuk imunisasi rutin, layanan seperti itu belum pernah hadir.
Memang, sebagian besar buruh harian lepas di PT SJAL telah didaftarkan ke dalam program BPJS Kesehatan oleh perusahaan. Namun menurut Yublina, ini belum cukup. Masih belum ada fasilitas kesehatan langsung di sekitar area kerja, apalagi dukungan nyata untuk pemenuhan hak kesehatan anak-anak buruh.
“Banyak anak buruh yang lahir di klinik, tapi tak sedikit juga yang lahir dengan bantuan dukun beranak. Itu menunjukkan lemahnya sistem layanan kesehatan dasar kita, terutama untuk ibu dan anak,” ungkapnya.
Lebih jauh, Yublina menilai perusahaan seharusnya turut mengambil peran aktif dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai, termasuk imunisasi. Selama ini, beban pemenuhan hak anak masih sepenuhnya ditanggung oleh orang tua.
Meski belum ditemukan kasus kematian anak akibat tidak diimunisasi, kasus kematian bayi karena pendarahan saat persalinan pernah terjadi yang menunjukkan celah besar dalam sistem layanan kesehatan di wilayah perkebunan.
Bantuan dari pemerintah, kata Yublina, juga belum konsisten. “Selama ini belum ada bantuan kesehatan yang berkelanjutan. Kalau tak ada yang bisa mengantar ke puskesmas, ya anak-anak tidak dibawa. Akhirnya imunisasi tertunda atau tidak dilakukan,” katanya.
Minimnya fasilitas umum seperti klinik desa atau mobil layanan kesehatan juga menambah beban. Dengan para suami sibuk bekerja dan tidak ada tempat penitipan anak, para ibu buruh harus mengandalkan diri sendiri untuk mengurus anak sekaligus mencari nafkah.
Fasilitas kesehatan di lingkungan perkebunan sawit Ketapang dan Sanggau dinilai masih jauh dari memadai. Menurut Teraju Indonesia, sebagian perusahaan hanya menyediakan layanan kesehatan sebatas memenuhi kewajiban administratif, tanpa memastikan kualitas dan akses yang layak. Buruh kerap mengaku belum pernah diperiksa, dan dalam kondisi darurat, mereka harus mencari kendaraan sendiri atau berobat seadanya. Pemeriksaan kehamilan pun seringkali dibebankan kepada ibu hamil, baik dari segi alat maupun biaya. Di beberapa lokasi, bahkan tidak tersedia posyandu atau klinik sama sekali.
Situasi ini memperlihatkan lemahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap kesehatan pekerja dan keluarganya. Minimnya dukungan institusional dan buruknya infrastruktur memperparah kesenjangan layanan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Padahal, Permentan No. 19 Tahun 2011 menegaskan bahwa penyediaan fasilitas kesehatan adalah kewajiban hukum perusahaan. Sayangnya, di lapangan, akses imunisasi dan layanan dasar lainnya masih menjadi perjuangan harian para ibu buruh di tengah medan berat kebun sawit.
Kami telah berupaya menghubungi pihak perusahaan untuk mengonfirmasi ketersediaan dan pelaksanaan regulasi terkait fasilitas kesehatan. Namun hingga laporan ini disusun, PT Rezeki Kencana Prima (RKP) belum memberikan tanggapan atas permintaan wawancara maupun klarifikasi.
Sementara itu, seorang buruh PT Sawit Jaya Abadi Lestari (SJAL) menyampaikan bahwa manajer terkait sedang cuti hingga awal Agustus. Kontak perusahaan, menurutnya, hanya dapat diberikan setelah mendapat izin langsung dari manajer tersebut.
Upaya Dinkes: Terbatas dan Belum Merata
Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Feria Kowira, imunisasi dasar lengkap (IDL) mencakup hepatitis B, BCG, polio oral dan injeksi, DPT-Hib-Hepatitis B, serta campak MR bagi anak usia 0–59 bulan. Namun, hingga pertengahan 2024, belum tersedia data spesifik terkait cakupan IDL di wilayah perkebunan sawit. Padahal, wilayah ini dihuni oleh ribuan buruh dan keluarganya, termasuk anak-anak yang berada dalam masa usia wajib imunisasi.
“Program kesehatan tidak semuanya terjangkau. Biasanya tetap harus dibantu oleh tenaga kesehatan dari perusahaan,” ujar Feria. Strategi yang diterapkan saat ini antara lain berupa pelayanan berkala dengan mendatangkan dokter spesialis dari RSUD untuk kegiatan imunisasi dan promosi kesehatan. Namun keterbatasan tenaga, logistik, serta akses geografis membuat kegiatan ini tidak dapat menjangkau seluruh area kebun dan tidak berlangsung secara rutin setiap bulan.
Peran posyandu dan puskesmas keliling memang sangat penting, terutama di lingkungan kebun yang minim fasilitas. Beberapa posyandu dijalankan oleh tenaga kesehatan perusahaan, namun vaksinnya tetap disuplai dari puskesmas pengampu. Sayangnya, kualitas layanan ini belum sepenuhnya terpantau, dan tidak semua perusahaan menjalankan fungsinya secara aktif.
Jika ditemukan anak yang belum diimunisasi, pelaporan biasanya berasal dari kader atau relawan posyandu. Anak akan langsung diberikan imunisasi sesuai dengan wilayah domisili kerja. Namun hingga kini, belum ada koordinasi lintas sektor yang berjalan efektif misalnya dengan Dinas Tenaga Kerja atau Dinas Sosial untuk menjamin perlindungan imunisasi anak buruh sawit secara menyeluruh.
“Belum ada,” jawab Feria singkat saat ditanya soal kerja sama lintas sektor tersebut.
Padahal, sesuai berdasarkan Permenkes No. 12 Tahun 2017, Dinas Kesehatan kabupaten/kota memiliki tanggung jawab memastikan ketersediaan dan keterjangkauan imunisasi bagi seluruh sasaran melalui berbagai fasilitas kesehatan, termasuk puskesmas, puskesmas keliling, posyandu, dan jejaring fasilitas kesehatan lainnya.
Lebih lanjut, regulasi ini juga menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib memastikan keberlangsungan program imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan, termasuk untuk kelompok rentan di wilayah-wilayah dengan hambatan geografis dan sosial.
Dalam konteks perkebunan sawit di Ketapang dan Sanggau, di mana ribuan anak buruh hidup jauh dari fasilitas kesehatan, regulasi ini seharusnya menjadi pijakan utama untuk mengintegrasikan layanan imunisasi ke dalam ekosistem kerja dan tempat tinggal buruh.
Untuk menutup kesenjangan, Dinkes Ketapang saat ini menjalankan program imunisasi kejar, menyasar anak usia 12–59 bulan yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Namun menurut Feria, program ini masih sangat terbatas dari sisi sumber daya manusia dan logistik vaksin, yang sebagian besar masih bergantung pada dukungan dari pemerintah pusat.
Ia pun mengakui adanya ketimpangan antara cakupan imunisasi di wilayah umum dengan wilayah perkebunan. Namun, Feria tetap menekankan pentingnya kesadaran dari para orang tua dalam memastikan anak mendapatkan imunisasi.
“Cakupan imunisasi kembali lagi ke orang tuanya,” ujarnya.
Padahal dari berbagai kisah lapangan seperti pengalaman Saras dan Ana di Sanggau terlihat bahwa kendala utama bukan semata persoalan kesadaran, melainkan hambatan struktural seperti minimnya fasilitas, jauhnya jarak, tidak adanya transportasi, serta lemahnya peran perusahaan dan pemerintah dalam menjangkau kelompok marjinal.
Situasi ini menunjukkan perlunya kebijakan publik yang lebih terkoordinasi dan responsif, tidak sekadar bertumpu pada program imunisasi rutin, melainkan juga melibatkan perumusan strategi lintas sektor antara Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Sosial, serta pelaku usaha di sektor swasta guna memastikan hak kesehatan anak-anak buruh sawit benar-benar terlindungi, sesuai amanat Permenkes No. 12 Tahun 2017 dan nilai-nilai keadilan sosial yang dijamin dalam konstitusi.
(Tulisan ini Didukung oleh AJI Indonesia dan Global Health Strategic)
disadur dari: https://www.puankhatulistiwa.com/imunisasi-di-kawasan-sawit-kesadaran-buruh-tinggi-fasilitas-masih-rendah/